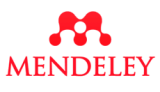PENGENALAN TANAMAN TRADISIONAL SUNDA SEBAGAI PENGOBATAN ALTERNATIF BAGI MAHASISWA BILINGUAL SUNDA-INDONESIA DI FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS PADJADJARAN: PERSPEKTIF DIALEKTOLOGI DAN EKOLINGUISTIK
Abstrak
Bahasa daerah memiliki kedudukan yang amat vital dalam kehidupan masyarakat daerahnya, yakni sebagai bahasa lokal dalam suatu suku, sebagai bahasa dalam kekayaan budaya daerah, dan sebagai bahasa dalam adat istiadat daerah. Dalam kedudukannya itu, bahasa merupakan warisan budaya takbenda, yakni warisan budaya dari tradisi dan ekspresi lisan masyarakat tuturnya. Secara praktis, bahasa daerah tidak hanya tecermin dalam praktik komunikasi sehari-hari, tetapi juga termanivestasi melalui teks-teks kuno, puisi, legenda, hikayat, peribahasa, dan cerita rakyat. Dalam kaitannya dengan hal ini, jika banyak kosakata bahasa Sunda yang hilang dan tidak lagi dipahami oleh generasi muda, akan sangat berdampak terhadap pemahaman masyarakat tutur atas macam bentuk kata yang dikandung oleh alam semesta. Atas dasar hal itu, mesti ada upaya serius untuk mengenalkan bahasa Sunda kepada generasi mutakhir agar tidak terjadi suatu kondisi yang dikhawatirkan oleh para linguis, yaitu adanya pergeseran bahasa atau bahkan kepunahan bahasa. Di sisi yang lain, kekayaan hayati yang dimiliki oleh masyarakat Sunda yang termanivestasi menjadi kekayaan kultural berupa praktik-praktik pengobatan tradisonal juga harus terus dilestarikan. Oleh sebab itu, urgensitas pemeliharaan dan revitalisasi bahasa dan budaya Sunda tersebut harus dilakukan, salah satunya melalui pengenalan tanaman tradisional Sunda sebagai pengobatan alternatif. Kegiatan pelatihan dilakukan secara sistematis, dari kegiatan yang bersifat teoretis hingga praktis, yaitu dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, praktik, dan brainstorming. Peserta pelatihan adalah mahasiswa bilingual Sunda-Indonesia di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran.
Referensi
Ayatrohaedi. (2002). Pedoman Penelitian Dialektologi. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
Ethnologue, S. I. of L. and. (2016). Ethnologue Language of The World. https://www.ethnologue.com/country/ID
Jennifer, H., & Saptutyningsih, E. (2015). Preferensi Individu Terhadap Pengobatan Tradisional di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan, 16(1), 26–41.
Mahsun. (2010). Genolinguistik: Kolaborasi Linguistik dengan Genetika dalam Pengelompokan Bahasa dan Populasi Penuturnya. Pustaka Pelajar.
Mbete, A. M. (2015). Pembelajaran Bahasa Berbasis Lingkungan: Perspektif Ekolinguistik. RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa, 1(2), 352–364.
Paoli, G. D., Wells, P. L., Meijaard, E., Struebig, M. J., Marshall, A. J., Obidzinski, K., Tan, A., Rafiastanto, A., Yaap, B., Slik, J. F., Morel, A., Perumal, B., Wielaard, N., Husson, S., & D’Arcy, L. (2010). Biodiversity Conservation in the REDD. Carbon Balance and Management, 5(7), 1–9.
Sobarna, C., Gunardi, G., & Wahya. (2018). Toponimi Nama Tempat Berbahasa Sunda di Kabupaten Banyumas. Panggung, 28(2), 147–160.
Subiyanto, A. (2013). Ekolinguistik: Model Analisis dan Penerapannya. Humanika, 18(2). https://doi.org/10.14710/humanika.18.2.
Tarigan, B. (2016). Kebertahanan dan Ketergeseran Leksikon Flora Bahasa Karo: Kajian Ekolinguistik. Universitas Sumatera Utara.
Wahya. (2015). Bunga Rampai Penelitian Bahasa dalam Perspektif Geografis. CV. Semiotika.
Zulaiha, I. (2010). Dialektologi: Dialek Geografi dan Dialek Sosial. Graha Ilmu.
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
##submission.copyrightStatement##
Jurnal ini Terindeks di:
PENERBIT
Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Padjadjaran