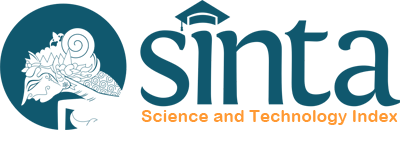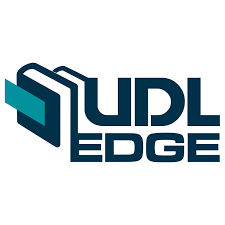MEKANISME MASYARAKAT LOKAL DALAM MENGENALI BENCANA DI KABUPATEN GARUT
Abstrak
Kabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Barat, yang dikenal masyarakat sebagai kawasan “mini market” bencana di Indonesia, sehingga layaknya masyarakat berupaya untuk dapat hidup selaras dengan berbagai potensi bencana alam yang ada dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas dalam menghadapi bencana. Memahami mekanisme masyarakat lokal dalam mengenali bencana adalah langkah awal yang perlu dilakukan untuk dapat menciptakan sistem mitigasi bencana berbasis masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder melalui teknik wawancara mendalam dan validasi data dilakukan dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan masyarakat Kabupaten Garut memiliki mekanisme dalam mengenali potensi terjadinya bencana, yaitu dengan menemukenali berbagai gejala yang terjadi sesuai dengan jenis bencana yang berpotensi terjadi. Kepercayaan, pengetahuan, kesadaran dan perilaku yang dimiliki oleh masyarakat lokal merupakan asset, terutama dalam upaya pencegahan terjadinya bencana (mitigasi bencana). Namun demikian, terkait kepercayaan dan ritual yang dulu dilakukan oleh masyarakat sebagai upaya pencegahan bencana, saat ini mulai luntur dan ditinggalkan karena dinilai bertentangan denagn keyakinan agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat setempat.
Kata Kunci
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Adimihardja, K. (2009). Leuweung titipan: Hutan Keramat Warga Kasepuhan di Gunung Halimu. Dalam Herwasono Soedjito et al. (Penyunting), Situs Keramat Alami. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Komite Nasional MAB Indonesia, LIPI dan Conservation International Indonesia, 78-85.
Amri, M.R., Yulianti, G., Yunus, R. Wiguna, S., Adi A.W., Ichwana, A.N., Randongkir R. E., Septian, R.T. (2016). Risiko Bencana Indonesia (RBI). BNPB
Ataupah. 2004. Peluang Pemberdayaan Keraifan Lokal Dalam Pembangunan Kehutanan. Kupang: Dephut Press.
Badan Nasioanl Penanggulangan Bencana. (2017). Info Bencana Desember 2016. Diakases tanggal 1 Agustus 2017 dari https://www.bnpb.go.id/uploads/publication/ info_bencana_desember_final.pdf.
Bappenas dengan BKNPB. (2006). Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Press.
Boedhihartono (2009). Tanah Toa, Kajang, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Dalam H. Soedjito et al. (Eds), Situs Keramat Alami. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Komite Nasional MAB Indonesia, LIPI dan Conservation International Indonesia, 62-77.
Buchari, A., Santoso, M. B., & Marlina, N. (2017). Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Desa Tanggung Bencana di Kabupaten Garut (Studi Kasus Di Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler). Jurnal Analisis dan Kebijakan Publik. Vol. 3 No. 1. Juni 2017. Hlm. 49-62
Darmanto. (2009). Pandangan tentang Hutan, Tempat Keramat, dan Perubahan Sosial di Pulau Siberut, Sumatera Barat. Dalam Herwasono Soedjito et al. (Eds), Situs Keramat Alami. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Komite Nasional MAB Indonesia, LIPI dan Conservation International Indonesia, 130-164.
Fauzi, H. (2006). “Memahami Fenomena Alam Pertanda Bencana”. Opini dalam Banjarmasin Post, 30 September 2006.
Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 131 tahun 2003 Tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah
Maarif, Syamsul. (2015). Sosiologi Kebencanaan dan Pengurangan Risiko Bencana Komunitas (Pengukuhan sebagai Guru Besar Sosiologi Kebencanaan). Jember: Universitas Jember
Maryani, Enok. (2008). Model Sosialisasi Mitigasi Pada Masyarakat Daerah Rawan Bencana di Jawa Barat. Bandung: Penelitian HIBAH DIKTI.
Maskud. (2016). Kearifan Lokal Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Fenomena, Vol. 15 No. 2. Oktober 2016
Noor, M. & Jumberi, A. (2007). Kearifan Budaya Lokal dalam Perspektif Pengembangan Pertanian di Lahan Rawa. Banjarbaru/Bogor: Balai Besar Sumber daya Lahan Pertanian.
Permana, R.C.E., Nasution, I.P. & Gunawijaya J. (2011). Kearifan Lokal Tentang Mitigasi Bencana Pada Masyarakat Baduy. Makara, Social Humaniora, Vol. 15 No. 1, Juli 2011. Hlm. 67-76
Purwanto, Y. (2009). Tempat Keramat Masyarakat Dani di Lembah Baliem” dalam Herwasono Soedjito dkk. (E) Situs Keramat Alami. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Komite Nasional MAB Indonesia, LIPI dan Conservation International Indonesia, 215-239.
Stanis, Stefanus. (2005). “Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Melalui Pemberdayaan Kearifan Lokal di Kabupaten Lembata, Propinsi Nusa Tenggara Timur”. Tesis. Tidak Dipublikasikan.
Sunaryo dan L. Joshi. (2003). Peranan Pengetahuan Ekologi Lokal dalam Sistem Agroforestri. World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Offive, Bogor, Indonesia
Suryowati, Estu. (2018). Sepanjang 2017, BNPB Mencatat 2.175 Kejadian Bencana di Indoensia. Harian Umum Nasional Kompas. Diunduh pada 19 September 2018 pukul 14.05 WIB.
Wahyono, A. (2001). Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. Yogyakarta: Media Pressindo.
Wikantiyoso, Respati. (2010). Mitigasi Bencana di Perkotaan; Adaptasi atau Antisipasi Perencanaan dan Perancangan Kota? (Potensi Kearifan Lokal Dalam Perencanaan dan Perancangan Kota Untuk Upaya Mitigasi Bencana). Local Wisdom. Vol. 2, No. 1. Hlm. 18-29, Januari 2010.
Zamzami, Lucky & Hendrawati. (2011). Kearifan Budaya Lokal Masyarakat Maritim Untuk Upaya Mitigasi Bencana Di Sumatera Barat. Padang: Lembaga Penelitian Universitas Andalas.
DOI: https://doi.org/10.24198/share.v8i2.18885
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.





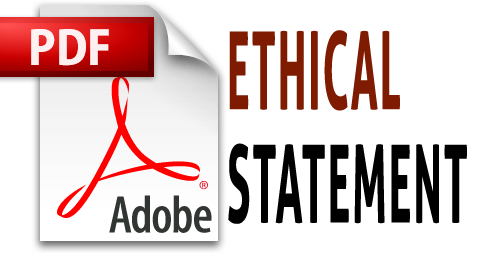
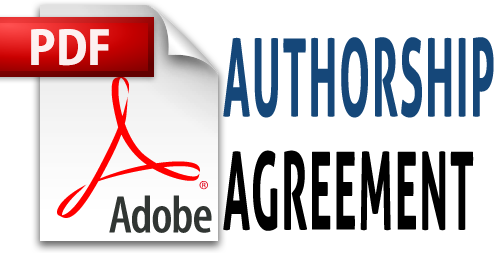
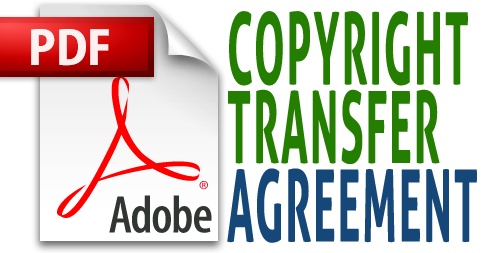

21.png)